Tinta Hitam
Harry Handika
Pepohonan
mengibas-ngibaskan ranting seraya mengamatiku tajam. Aku termenung dalam
dekapan kesengsaraan yang kini menderaku. Dedaunan berjatuhan pelan, kadangkala
mengenai kepalaku yang sedang semrawut. Di bawah pohon beringin ini yang begitu
rindang, aku seperti dibuat nyaman olehnya. Acap kali aku bertengger di atas
batu hitam yang teronggok bisu di bawah beringin ini, aku selalu teringat semua
kejadian-kejadian itu. Aku kacau, tak jarang aku mencurahkan isi hatiku kepada
burung-burung yang lalu-lalang meraba pepohonan.
“Doni!
Cepat ke pasar, persediaan makanan sudah habis!” ungkap majikanku sambil
melemparkan uang ke muka lantai.
“Siap,
Nyonya,” jawabku pelan dan langsung menurut.
Yang aku tahu selama ini, majikanku
adalah seorang binatang buas yang terkadang jinak. Terkadang ia berhati
malaikat, tetapi bisa menjadi iblis yang terkutuk. Nyonya Merry hidup sendiri,
menurut cerita Bi Minah yang sudah merawatku hingga sekarang, seseorang yang
dengan sukarela membesarkanku yang yatim piatu, tuturnya Nyonya Merry telah ditinggalkan
suaminya yang gugur dalam tugas. Suaminya meupakan seorang tentara yang ditempatkan
di daerah konflik. Mungkin ia berhati keras karena dulu jarang mendapat
perhatian dari suaminya itu.
***
Aku kembali dengan membawa barang
belanjaan yang begitu banyak, tulang-tulangku serasa remuk membawa belanjaan
sebanyak itu. Ketika membuka pintu, rumah terlihat sepi. Hanya suara perempuan menangis
pelan yang kudengar. Di pojok sebelah kanan, di kursi goyang dekat akuarium.
Nyonya Merry rupanya kembali menduka, setiap tanggal 6 ia selalu menangis di
situ, tepat di situ. Terpajang potret-potret suaminya yang memakai seragam
tentara lengkap. Suaminya terlihat gagah, senyum bahagia mengembang dari bibir
Nyonya Merry yang berdiri di sampingnya. Mereka bergandengan tangan, sungguh
serasi menurutku. Setiap Nyonya Merry menangis, foto-foto itu selalu dipandanginya. Namun ada satu foto yang tertutup kain hitam,
tak ada yang boleh membukanya.
“Nyonya,
ini belanjaannya.”
“Taruh
saja di situ,” ungkapnya tersendat-sendat menahan tangis.
Sebenarnya aku merasa kasihan
dengannya. Ia hidup sendiri, hanya aku dan Bi Minah yang setia menemaninya.
Guratan duka terlihat sangat menggores lubuk hatinya. Nyonya Merry jarang ke
luar rumah, saban hari ia memenjarakan dirinya di rumah megah ini. Orang tuanya
dulu, adalah seorang yang kaya raya, begitulah cerita dari Bi Minah. Pernah
suatu hari aku dan Nyonya Merry duduk bersama di dekat kolam. Ia menceritakan
semua yang ia rasakan, kesepian dan kehilangan. Ia hanya punya satu hal yang
paling berharga, harta karunnya, ya harta karun yang selalu disebut-sebutnya
itu. Aku tak paham dengan celotehannya itu.
“Aku
hanya punya harta karun!”
“Harta
karun seperti apa Nyonya?” tanyaku penasaran.
“Mmmm..”
Dia hanya membisu.
Nasibku tak jauh berbeda dengannya,
aku juga hidup sebatangkara. Mengabdikan hidup di rumah janda tua yang
ditinggal mati suaminya. Kami di sini bagaikan terkurung di dalam sangkar.
Sangat jarang canda tawa yang ada di rumah ini. Hanya keluh kesah dan duka yang
menyelimuti rumah ini.
***
Hari ini, aku tidak melihat Nyonya
sejak pagi. Biasanya ia duduk di kursi goyang itu di sela-sela harinya yang
malang. Namun hari ini kursi goyang itu hanya terdiam tak bergeming. Aku
menanyakannya pada Bi Minah, ia juga tak melihatnya. Aku melanjutkan untuk
membersihkan perabotan rumah, aku terhenti ketika memandangi foto Nyonya Merry
dan suaminya. Kebahagiannya seakan terenggut, senyumnya tak pernah mengembang
lagi. Kini, sayap-sayap kehidupannya telah patah, terombang-ambing di atas
angin.
Hingga malam larut Nyonya masih tak
terlihat, aku berniat menilik ke kamarnya. Pernah sekali aku masuk ke kamarnya,
di dalamnya penuh dengan foto-fotonya sewaktu masih muda. Pintu kamarnya
tertutup. Aku membukanya perlahan, tak terkunci. Aku terkejut! Mulutku menganga
lebar, darahku seakan berhenti berdesir. Mataku tak berkedip, di depanku telah
tercecer darah segar yang mengalir dari atas kasur. Aku panik, aku segera
memanggil Bi Minah.
Bi
Minah menangis histeris. Dengan ketakutan aku mendekat. Pisau dapur telah
merobek tangan Nyonya Merry. Pisau itu masih dalam genggamannya walau tak erat.
Secarik kertas terbuka di sampingnya, lalu aku membacanya.
“Doni,
maafkanlah saya. Saya telah terpuruk dengan semua ini, saya sudah tidak tahan.
Maafkanlah saya, saya tidak bisa menjadi Ibu yang baik untukmu. Kau adalah anakku,
harta karunku selama ini, jika tidak percaya bukalah foto itu. Foto yang selalu
tertutup. Kau akan tahu dari sana, aku titipkan engkau kepada Bi Minah. Selamat
tinggal anakku, selamat tinggal dunia.” Begitulah isi kertas itu, aku terkejut
dan tak percaya. Aku bergegas mengambil foto itu.
Aku membuka kain penutupnya.
Terlihat Nyonya Merry dan suaminya, namun ada yang berbeda. Nyonya Merry
menggendong seorang bayi dalam pangkuannya. Tepat di tangan sebelah kiri bayi
itu, ada tompel. Aku melihat tanganku, sama persis dengan bayi dalam foto ini.
Aku memeluknya yang telah bersimbah darah.
Setelah kejadian itu, aku selalu
merenungi hidupku. Mengabadikan semua hal yang ku alami. Di atas kertas dengan menggoreskan
tinta hitam.
***
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

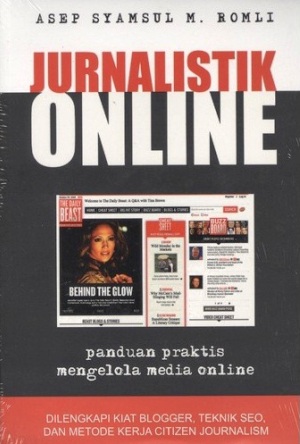

1 Comments for "Tinta Hitam - Harry Handika - Lomba Menulis Cerpen"
cerpennya cukup menarik dan sangat mengejutkan pad endingnya