BERLIAN LAPUK
Tiara Cahyani Ayu
Ningrum
“Rapi amat pakaiannya
mbak,” rupanya teguran yang baru saja kulontarkan kepada teman satu SMA-ku dulu, telah membuat bola
matanya sedikit membesar.
“Eh Carla. Iyanih, kan mau ke STAIN. Kamu sendiri
gak daftar kuliah?”
Aku
mengumpulkan sedikit udara di dalam mulut hingga terlihat seperti balon kecil.
Lalu, kukeluarkan kembali ke daerah asalnya. Beberapa waktu kemudian, aku pun kembali membuka mulut
untuk mengeluarkan beberapa jawaban. Percakapan itu tetap kulanjutkan walau tak begitu
menarik.
“Ya. Aku akan ikut denganmu, tapi…,” tapi aku tak ingin menghadapi kegiatan
membosankan itu! Tak kulanjutkan. Bukan karena takut dengannya, namun hanya sedikit
menghindari percakapan yang semakin
panjang dan menyiksaku.
“Tapi?”
“Tapi, aku harus bertemu dulu dengan lelaki itu dan
membicarakan hal ini kepadanya.” lagi-lagi aku tak ingin terlalu berterus
terang akan tujuan dari kata tapi
barusan.
“Maksudmu, kau ingin meminta izin dulu kepada
ayahmu? Pergilah, aku akan menunggumu di sana.” Ujarnya sembari mengarahkan
jari telunjuknya menuju sebuah kursi panjang yang terletak di salah satu sudut
taman kompleks rumahku.
Ya, dia telah di sana. Menunggu aku yang belum
saja kembali ke hadapannya. Dan memang ku
takkan kembali. Seharusnya aku peduli terhadap
Azura yang kubuat menunggu sedari tadi.
***
Hari ini aku kembali tenang. Ayah telah mendaftarkan
diriku ke salah satu tempat kuliah di kotaku ini. Kurasa Azura telah menyebut
nama tempat itu, dan tentu tak perlu kusebut kembali.
Namun, sayangnya keberuntungan tak berpihak padaku
kali ini. Tuhan telah mengutukku. Mengutuk keluargaku. Lelaki itu sangat
terpuruk di hadapanku kali ini. Tak pernah kulihat ia meneteskan air mata,
kecuali pada detik ini.
“Aku telah gagal,” gumamnya lirih.
Kesedihan telah menyelimuti dirinya dengan begitu
rapat namun hangat. Penyesalan. Hanya itu yang dapat kudeskrepsikan kepada
lelaki yang telah tertunduk kaku di hadapanku sejak beberapa waktu lalu.
Awalnya, pertanyaan-pertanyaan aneh nan bernada tengah bersorak di kepalaku. Penyesalan? Mengapa? Ia menangis? Ada apa
ini? Seperti itu. Peri Tanya telah menatapku dengan mata membelalak. Sesaat
setelahnya aku belum juga paham.
“Aku sudah menyogok petugas, guru, hingga kepala di
sana. Namun, tak ada yang peduli. Bagi mereka pengetahuan bukanlah uang. Dan
memang selayaknya seperti itu. Kau sabar ya nak, perusahaanku juga sudah tak
ada lagi yang dapat diharapkan
darinya.”
“Kau lihat? Ayahmu telah berkorban begitu banyak
untukmu! Tapi kau? Kau tak pernah menghargai sedikit pun dari apa yang telah
ia korbankan terhadapmu! Sekarang tak ada harapan lagi. Jika aku dan ayahmu
terus membiarkan dirimu berada di sini, kami akan ikut hancur. Kami
tak ingin hancur bersamamu. Kau
tak punya apa-apa.”
Suara melengking itu nyaris membuat diri ini
terhempas hingga ke luar angkasa bersama space
rubbish yang akan dilenyapkan. Melihat tentang siapa yang telah berani
membentakku tadi, refleks saja diriku melakukan eye rolling.
***
Aku kewalahan di tengah hujaman titik-titik air yang
mengarah kepadaku. Perempuan
itu telah mengenyahkan bayanganku dari
sana, di rumah itu. Satu-satunya tempat di mana aku mengenang almarhum ibu,
kini telah lenyap dari kehidupanku. Tak ada lagi bayang-bayang ibu yang sering
kali kulihat di pojok kamar. Tak ada lagi wajah cantiknya yang tersenyum
kepadaku. Ya sudahlah, aku pun tak dapat mengulang waktu kembali.
***
Kini usiaku telah melewati masa remaja. Masa yang
kulalui dengan suka cita. Di mana suka, duka, kebahagiaan, kesedihan, kepiluan,
dan kepedihan telah menghujamiku dengan sebukit pertanyaan yang aneh meski
nyata. Akupun memutuskan untuk
memilih profesi layaknya orang yang tengah berputus asa. Menyodorkan tangan
kosong yang berharap diberi selembar uang,
mengeluarkan nada pilu, serta kadang kala aku memasang kecacatan palsu demi
menarik rasa kasihan dari orang-orang
itu. Hari semakin terik. Kusandarkan bahu lemasku menuju kursi plastik di tepi
jalan.
“Apa yang kau lakukan di sini wahai nenek manis?” tanya seorang gadis
kecil sembari sedikit menepuk pundakku. Suaranya yang lantang bin lembut nyaris
membuat bola mataku membesar, namun kutahan.
“Eh, ti-tidak. Aku hanya sedang menatap indahnya
kota,” jawabku terkaku.
“Mengapa kau meminta uang kepada orang-orang itu?”
“Aku membutuhkannya…” sekali lagi aku menjawab
dengan nada pelan. Sangat pelan.
“Untuk apa?”
“Makan.”
“Mengapa kau tak memilih pekerjaan yang lebih
berwibawa?”
“Kau ini banyak tanya sekali. Baiklah, aku tak punya
pekerjaan. Aku tak punya modal untuk itu. Aku tak menyelesaikan kuliahku. Tepatnya,
aku gagal mendaftarkan diri.”
“Mengapa
tak kau coba lagi? Well, aku tahu usiamu sudah lewat dari masa kewajaran. Ingat, ilmu
tak pernah memandang usia. Maukah kau ikut denganku?”
“Ke mana?”
“Perpustakaan kota.”
“Tempat apa itu? Aku tak pernah ke sana sebelumnya…”
“Kali ini kau akan ke sana,” ujarnya meyakinkan.
Ia menarik tanganku dengan kuat hingga aku sedikit tersentak kemudian berlari.
Tak lama aku menyusuri tiap bagian kota ini, di
hadapanku telah terlihat bangunan sederhana namun besar kelihatannya.
“Yuk nek, kita masuk.”
Aku menuruti perkataannya. Kupandangi seisi bangunan
itu, menyusuri tiap lemari yang berisikan deretan buku-buku tebal dan tipis,
meraba tiap lembaran buku-buku itu. Buku yang dahulu kuhina, kucaci, dan kumaki
tampak berbeda di sini.
***
Setahun berlalu. Aku merasa bahwa diriku telah
menguasai materi ‘Sastra dan Bahasa’ yang tiap hari kuamati di perpustakaan
kota itu. Entah apa yang telah menarik kakiku menuju salah satu tempat yang tak
asing bagi mahasiswa di kota ini,
STAIN. Aku
memang pernah mendaftar di sini sejak puluhan tahun silam. Namun, aku tak
pernah menyimpan dendam pada tempat ini. Kucoba
memberanikan diri untuk masuk menyusuri tiap gerbang di sana. Aku mencoba
mengambil salah satu dari selebaran
formulir itu, kubawa pulang hingga mengisi poin
demi poin pertanyaan tersebut. Kemudian, kukumpulkan selebaran itu esok pagi.
Hari uji pengetahuan pun tiba. Aku diletakkan pada
ruangan tiga dan duduk paling depan. Sesaat aku merasa malu. Mereka mengejek
keadaan fisikku, memerhatikan lapisan kulitku, menatap setiap helai rambutku,
lalu tertawa terbahak-bahak.
“Hai nenek manis…,” cemooh salah satu dari mereka
sembari tertawa.
Ilmu tak pernah
memandang usia. Aku terkesiap. Kalimat itu seakan
mengageti batin. Tanpa menoleh ke arah mereka yang mengolok-olokku, dengan
lincah pena di tanganku seakan menari di atas kolom-kolom tempat jawaban yang
telah disediakan.
“aku yakin
sekali, ini benar-benar tepat!” gumamku bangga.
Tak puas dengan semua itu. Aku kembali membaca,
meneliti setiap kata dan kalimat yang telah kugoreskan di atasnya hingga
benar-benar yakin akan apa yang telah kutuliskan di sana, kemudian kuserahkan kepada pengawas ruangan.
“Luar biasa…” ia bergumam sembari menatapku
dalam-dalam
“Ada apa? Ada yang salah dengan jawabanku? Ataukah
penulisan namaku? Biarkan aku merevisinya. Maklum, mata ini sudah tak layak
pakai tanpa kaca mata.”
“Tak
ada yang salah,” kalimatnya terpotong oleh gerakan kepala.
“Baik, semuanya harap mengumpulkan pekerjaan lima menit lagi.
Dan kau, nenek. Silahkan pulang dan menunggu hasilmu.”
***
Aku berada di tengah kerumunan jiwa yang penasaran.
Badanku terbilang rapuh. Namun, tak menggoyahkan semangat yang membara di dada.
Aku menatap selebaran yang direkatkan pada papan pengumuman yang berisi
nama-nama calon mahasiswa baru di sini. Tak kutemukan namaku. Beranjak pada
selebaran kedua di sebelah kanannya, hingga menemukan nama Sania Carla Renata. Ya, Tuhan! Aku
berhasil? Tell me if I’m dreaming! Kucubit kulit pipiku yang kerut. Ah! Ini sakit. Aku tak bermimpi.
Sejak keberhasilan itu menyapaku, kini aku sadar bahwa
perbuatan itu adalah perbuatan terbodoh yang pernah dilakukan oleh manusia
sepertiku. Gadis itu telah membangunkan
raga ini dari indahnya mimpi sesat itu. Ia telah
menemukan julukan yang pas untukku. Namun sayang, aku tak sempat menanyakan nama dan
tempat tinggalnya. Tapi aneh, semenjak ia meninggalkanku pada hari itu, ia tak
pernah lagi kutemukan dalam bangunan kokoh itu. Tiap hari kusempatkan untuk ke
sana. Menyusuri tiap lemari. Lemari yang telah membuka mataku dari seruan gadis
kecil manis. Tak pernah kusangka, ending
kehidupanku akan secerah ini. Secerah berlian. Berlian yang telah lapuk akan
kikisan kecurangan.
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

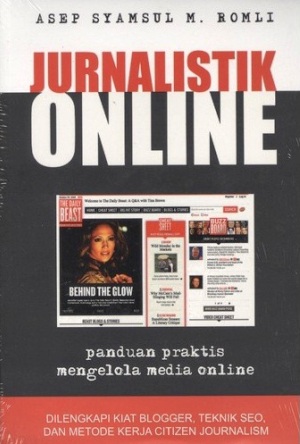

0 Comments for "BERLIAN LAPUK - Tiara Cahyani Ayu Ningrum - Lomba Menulis Cerpen"