
Kali ini saya akan membagikan sebuah
cerpen yang saya dapatkan dari koran kompas. Cerpen bertema...... (saya sendiri
sulit menentukan temanya. Silahkan cari sendiri temanya). Cerpen ini sudah
diterbitkan di koran kompas. Yang penting ceritanya sangat, sangat, sangat
menarik. Selamat menikmati!
Untuk mendownload, klik link dibawah
Cerpen
Kompas: “Requiem”
Sebelum mati, aku masih ingat tubuhku
melenting: kakiku berkelejotan mencari tumpuan, sedangkan kepalaku menjadi
tumpuan di ujung lainnya. Lalu seluruh tubuhku meregang, seolah menolak
kehendak malaikat maut yang membetot nyawaku.
Waktu itu, samar masih kudengar tik-tak
jam di dinding kamar. Suaranya seperti sebuah requiem. Kemudian secara
perlahan-lahan aku melihat kaki, tangan, kepala, dan seluruh tubuhku melayang…
Ketika berhasil berdiri, istriku tampak
sibuk memencet-mencet tombol telepon. Aku juga masih ingat ketika kemudian
keponakanku membopong tubuhku sendirian menuju mobil yang dipinjam dari
tetangga. Ia bergegas memanggil Magenta, istriku, untuk memangku kepalaku di
jok belakang.
Dalam 30 menit, mobil sudah sampai di
ruang ICU sebuah rumah sakit. Waktu aku dibaringkan di tempat tidur dan
selang-selang dipasang di tangan serta mulutku, aku sebenarnya tak berharap
untuk hidup kembali.
Magenta mungkin tak tahu bahwa aku
menangis di bahunya, ketika ia hampir-hampir histeris meminta agar dokter
segera memberi pertolongan. Air mataku bahkan membasahi sebagian baju tidur
yang dikenakannya malam itu. Mungkin ia mengira itu keringatnya sendiri yang keluar
karena tegang dan putus harapan menyaksikan penderitaanku.
Dokter aku lihat geleng-geleng kepala.
Hanya mungkin karena gelengannya perlahan, Magenta tak begitu memerhatikannya.
Tetapi ketika ia berucap, ”Ibu yang tabah ya…. Ini mungkin hanya cobaan awal,”
istriku mulai meraung. Selain menuding-nuding para medis yang dinilainya tak
becus memberi pertolongan, Magenta juga membentak-bentak keponakanku. Ia
menuduh keponakanku sengaja melambat-lambatkan laju mobil agar nyawaku tidak
tertolong. Padahal aku tahu, keponakanku itu sudah menginjak pedal gas
sedalam-dalamnya. Tetapi karena jalanan yang berlubang, maka mobil terpaksa
dizig-zag. Zig-zag itulah menurut Magenta sebagai cara keponakanku untuk
memperlambat waktu tiba di rumah sakit.
Ketika Magenta mulai agak tenang,
kudengar dokter berbisik di telingaku, ”Kamu mesti temukan jalanmu. Kalau
ketemu persimpangan, lurus terus, terus, nanti di depan ada gerbang besar
dengan seorang berambut aneh yang menjaganya.” Lalu ia minta bicara berdua
dengan Magenta di ruangan sebelah yang hanya dibatasi tirai putih.
Tiba-tiba tik-tak jam dinding lagi-lagi
terdengar seperti requiem yang dikomposisi khusus buatku. Nada-nada yang
mengalir perlahan mencopoti tubuhku bagian demi bagian. Dengan latar awan dan
langit yang beku, aku seperti benda yang tak memiliki gravitasi. Cuaca di sini
begitu dingin. Matahari hanya sebentuk benda lembut yang beku. Sinarnya adalah
selang-selang yang meneteskan serpihan es. Ketika kurasakan angin perlahan
berembus, tubuhku malah terseret makin jauh… dan tersedot ke dalam lubang hitam
yang dalam.
Terakhir aku dengar dokter berkata
kepada Magenta bahwa aku telah mati karena gula darah yang anjlok. ”Ibu
terlambat membawa dia kemari. Tubuh suami Ibu meregang karena gula darahnya
anjlok. Ia pingsan sudah terlalu lama…. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,
kecuali berharap Ibu tetap tabah. Suami Ibu hanya pulang….”
”Apakah seorang dokter harus
mengucapkan kata yang sama dengan seorang pendeta di saat-saat seperti ini?”
teriak Magenta. Ah, perempuan itu memang jarang memikirkan kata-katanya sebelum
diucapkan. Ia tak berpikir bisa saja dokter marah kepadanya. Dan jasadku akan
terkatung-katung di rumah sakit ini.
Mereka bisa saja berpura-pura ingin
tahu penyakit apa sebenarnya yang membunuhku. Lalu melakukan otopsi dengan
mengiris-iris bagian demi bagian jasadku yang sudah kurus ini. Ah, pastilah
sangat mengerikan menyaksikan tubuh sendiri diiris-iris dengan pisau-pisau yang
besar….
”Seorang dokter atau pendeta bukankah
hanya dibedakan oleh jenis pekerjaannya,” jawab dokter kemudian dengan maksud
menenangkan. Magenta tercenung. Ia menghentikan teriakannya, kemudian lunglai
menggelesot di lantai…. Aku kasihan padanya.
Kata-kata dokter itu benar juga. Ketika
tadi aku berjalan lurus setelah bertemu dengan persimpangan, aku kini sampai di
sebuah pintu besar berukir dengan motif dedaunan dan bunga. Tak jelas benar
berfungsi sebagai apa gerbang itu, karena ia seperti digantungkan begitu saja
di serpih awan. Sedekat ini, aku hanya melihat seorang tua renta dengan tongkat
kepala naga. Ia berdiri tepat di tengah belahan kedua daun pintu.
Lelaki tua itu tak menegur dan hanya
berucap pelan, ”Dosamu terlalu banyak, kembalilah.” Aku tak mengerti, yang
kuingat kemudian aku mungkin sudah bertahun-tahun berjalan untuk menggapai
gerbang itu. Kulintasi segala gurun, lembah, hutan dan hujan, segala terik dan
batu-batu, belum juga aku mampu melewatinya. Bahkan aku pernah terombang-ambing
dalam amukan badai petir dan kilat yang berkecamuk seperti menerkamku. Toh aku
masih di sini, tetap berada di depan pintu.
Tetapi apakah dokter itu pernah mati?
Kalau begitu aku makin paham sekarang, bahwa benar belaka kematian bukan akhir
dari segala kehidupan. Sekarang ketika aku kembali di sini menjadi seekor
anjing, segalanya masih kuingat. Aku masih ingat perempuan tua yang menjadi
majikan besarku sekarang tak lain adalah Magenta. Mungkin usianya sudah mencapai
80 tahun, tetapi ia masih bersikeras tak mau menggunakan kursi roda.
Hari Minggu lalu, ketika ia jatuh di
kamar mandi dan aku berteriak-teriak mengabarkannya kepada seluruh penghuni
rumah, Marjolin, cucu perempuan kesayangan Magenta, sudah mengusulkan agar ia
memakai kursi roda pemberian kakek. Entah mengapa Marjolin punya kepedulian
yang begitu dalam terhadap kursi roda itu. Kursi roda itulah yang pernah
kuhadiahkan kepada Magenta ketika ulang tahun perkawinan kami yang ketujuh. Aku
ingat, ia marah-marah dan menuduhku mengada-ada. Kursi itu, katanya, semacam
doa pengharapanku agar ia lumpuh. Kemudian aku bisa bebas bersenang-senang
dengan perempuan lain.
”Kamu ini suami aneh, kok justru
mengharapkan istrinya duduk di kursi roda. Kalau maksudnya agar kamu lebih
bebas bermain-main dengan perempuan lain, tak perlu pakai cara-cara halus
seperti ini,” kata Magenta. Ketika melihat aku tak bereaksi dan tenang saja
menggosok gigi di wastafel dekat kamar mandi, setengah berteriak Magenta
bilang, ”Potong saja kakiku, kalau itu maumu…!”
Sekarang aku menyesal karena waktu itu
berpura-pura tak mendengar. Mestinya aku tahu perkataan Magenta itu, sebagai
bukti betapa dalam cintanya kepadaku. Seharusnya aku berusaha menjelaskan bahwa
hadiah kursi roda itu pun juga sebagai bentuk pernyataan cinta sejatiku
kepadanya. Kursi roda hanya simbol bahwa aku ingin hidup dengannya sampai tua
nanti. Sampai kami berdua benar-benar tak bisa berjalan dengan kaki kami
sendiri.
Rasa penyesalan yang dalam serta
keinginan kuat untuk menebus kesalahan kepada Magenta itulah, barangkali yang
membuat aku tetap bisa bersamanya sampai kini. Usia kami jauh berbeda. Magenta
sekarang sudah 80 tahun, sementara aku belum genap lima tahun. Kehadiranku
dalam keluarga ini berkat rasa belas kasihan Marjolin yang memungut aku dari
got di depan rumahnya.
Ketika usiaku baru satu hari, majikanku
pertama, yang tinggal di sebuah gang sempit di belakang rumah Magenta,
membuangku ke dalam got. Aku dengar dia bilang, anjing betina tidak terlalu
berguna, paling-paling hanya bikin rusuh kampung. Ketika musim kawin tiba,
anjing-anjing jantan akan berkeliaran di sekitar gang. Belum lagi, katanya,
kalau aku kawin dengan cara berenteng-renteng, akan menambah heboh seluruh
kampung.
Ketika Magenta jatuh untuk ketiga
kalinya, ia benar-benar tak bisa menolak saran Marjolin. Kursi roda yang selama
ini diletakkan di samping kursi lainnya, di mana Magenta biasanya menonton
televisi, terpaksa ia pakai. Dan itulah puncak kebahagiaanku. Magenta tampak
mencoba menggeser-geser roda kursi beberapa kali. Ia bahkan beberapa lama
sempat berkeliling ruangan. Diam-diam aku mendekat dan menjilati kakinya.
Mudah-mudahan ia ingat, hal yang sama pernah kulakukan ketika malam pertama
pernikahan kami.
Aku masih ingat benar bagaimana Magenta
menjerit-jerit manja sembari mengatakan geli. Kami lantas bergumul semalaman
sampai matahari benar-benar menembus celah gorden warna cerah kesukaannya.
Sekarang Magenta hanya mengelus kepalaku. Itu pun kuperhatikan tidak
sungguh-sungguh karena tangannya yang lain sibuk memencet-mencet tombol remote
control televisi. Tetapi aku ingat, gerakan jarinya persis seperti ketika ia
memencet-mencet tombol handphone sesaat sebelum aku mati.
Ketika ia menemukan channel yang
menurutnya pantas dilihat oleh seluruh anggota keluarga, Magenta
berteriak-teriak panik. Berkali-kali ia memanggil Marjolin, yang kebetulan saat
itu sedang di kamar mandi. Aku lihat di televisi orang-orang panik, sementara
sebuah gedung tampak terbakar. Asap hitam mengepul di antara puing-puing kaca serta
mobil-mobil yang terbakar.
”Jolin, cepat… aku sudah jemu jadi
saksi atas semua ketidakadilan ini. Bom meledak lagi. Ah, Tuhan, mengapa sejak
dulu aku hanya jadi saksi dari kematian demi kematian. Jolin, besok pesankan
saja peti mati dan sepetak tanah kuburan. Aku sudah lelah disuguhi kiamat
semacam ini…,” Karena Marjolin tak juga keluar, aku menggedor-gedor pintu kamar
mandi dengan kakiku.
”Jolin… cepatlah. Jangan biarkan aku
sendirian menjadi saksi…,” teriak Magenta histeris. Ia tampak tak berdaya,
bahkan sekadar mengganti channel televisi pun ia tak sanggup.
”Ada apa, Oma?” buru-buru tanya
Marjolin sesaat kemudian.
”Aku tak sanggup lagi disuguhi kematian
demi kematian. Sejak kakekmu mati mendadak dulu, seperti tak ada harapan lagi
buatku untuk hidup. Besok kamu pergi ke pasar, pesankan aku peti mati dan bunga
dukacita atas namaku sendiri….”
Sebelum Marjolin berkata aku meraung di
kaki Magenta, persis sewaktu ia mendengar rintihanku saat-saat menghadapi maut.
Mungkin ia tak pernah sadar kalau aku benar-benar menangis seperti bayi yang
kaget melihat dunia. Aku juga kaget, mengapa secepat itu harus mati dengan cara
yang menyakitkan banyak hati.
”Oma? Oma… sadar Oma…,” Marjolin
histeris melihat Magenta lunglai di atas kursi roda. Secepat kilat aku berlari
keliling rumah dengan maksud mengabarkan keadaan Magenta. Setelah melihat
seluruh ruangan kosong, aku berlari ke depan rumah mencari pertolongan. Tetapi
tak seorang pun tampak.
Aku malah berjumpa seorang tua dengan
tongkat kepala naga yang kutemui dulu di gerbang yang besar itu. ”Ia sudah
lelah, sudah saatnya kembali. Relakan saja…. Kamu harus di sini, sampai
benar-benar terbebas dari ikatan duniawi,” katanya.
”Apakah Anda malaikat?” tanyaku.
”Bukan, aku seseorang yang selalu
membawa buku besar tentang segala perbuatan manusia, termasuk segala prilakumu
saat kau terlahir seperti sekarang?”
”Terlalu besarkah dosaku di masa lalu
sehingga terlahir sebagai anjing?” tanyaku mengambil kesempatan. Lelaki tua itu
tak menjawab. Ia tiba-tiba melayang memasuki rumah kami. Di ruang dalam, Marjolin
menangis sejadi-jadinya, saat yakin Magenta telah tiada. Ia tak tahu kalau
lelaki tua bertongkat kepala naga itu telah membawanya melayang, melewati
kisi-kisi jendela.
Aku paham sekarang mengapa Derida,
suamiku, meregangkan tubuhnya ketika menghadapi maut dulu. Itulah rupanya cara
dia melawan kehendak waktu. Sewaktu ruhku meloncat dari tubuhku, aku dengar
tik-tak jam yang kupajang di atas televisi, menjadi requiem yang mengantar
kepergianku. Aku juga tahu, Derida berlari-lari ke setiap kamar dan ke halaman
untuk mencari pertolongan. Itu juga cara dia untuk melawan malaikat maut yang
hendak menjemputku.
Mungkin karena kehendak untuk terus
melawan tanpa henti itu, ia terlahir sebagai anjing. Padahal aku tahu, selama
ini ia begitu setia, lelaki yang memendam merahnya cinta seumur-umur sampai
harus mengada dalam wujud yang sangat terlambat kukenali.
Tag :
Cerpen


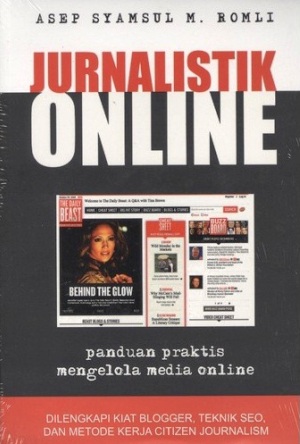

1 Comments for "Cerpen Kompas: “Requiem”"
pertamaxxxx.