Bukan Orang-orangan Sawah
Madhika Ekatra
Semua
tak akan bisa melihatnya, tapi begitu terasa bila didekatnya. Suara gemericik
dedaunan pohon serta gerakan melambai ringan dari orang-orangan sawah mungkin
dapat dijadikan pertanda kedatangannya, ya itulah angin. Orang-orangan sawah
pun membutuhkannya untuk sekedar terlihat hidup, seperti aku yang selalu
membutuhkannya hingga saat ini.
Hidup di desa mungkin kadang tak seindah pemandangannya,
hidup di kota pun mungkin tak semenyenangkan bayangan orang-orang yang belum
pernah dan ingin ke sana. Namun, semua bergantung pada persepsi kita. Persepsi
mungkin berbeda, tapi sebuah pengalaman dapat menghilangkan kemungkinan menjadi
kepastian dari perbedaan. Karena hidup kita menciptakan sejarah, yang tak mungkin
sama meski tak terpisah oleh jarak dan waktu di mana pun dan kapan pun.
Pagi ini tak seperti biasa, awan mendung menutupi
sinarnya yang biasa terpancar lucu menyoroti boneka tak berkaki di tengah
hamparan padi yang mulai menguning. Tak terasa sudah lima hari aku di sini,
tempat yang kuanggap sebagai rumah kedua. Besok mungkin aku akan pulang kembali
ke rumahku di Jakarta.
Aku merasa seperti orang-orangan sawah yang hanya bisa
diam mengikuti arah angin. Ayah selalu berpindah-pindah karena tuntutan pekerjaan
sedangkan ibu bisa dipastikan selalu ikut dengan ayah. Liburan di kampung
halaman ayah yang sebentar lagi berakhir ini merupakan waktu langka bersama
keluarga yang sulit direalisasikan di hari-hari biasa.
Terhitung aku dan Nirasha adikku, sudah tiga kali
berpindah-pindah sekolah. Seperti tertancap di tengah sawah, butuh dorongan
angin yang begitu kuat yang dapat melemparkanku sehingga bisa menemukan yang
tertancap lainnya untuk bisa sekedar dekat lebih lama. Jarak seakan menjadi
penghambat yang sangat lumrah meski dekat sedang menghampiri.
Meow…
suara kucing liar menghentakkanku dari lamunan tak berarti ini, seakan memaksa
untuk bangkit dari kursi goyang yang begitu membuatku nyaman. Setelah sarapan
aku segera kembali pada tahta kerajaan, ya kursi goyang yang terbuat dari
rotan. Kursi ini seakan menjadi pelarian dari cabang lanjutan dari sebuah
percakapan. “Kak…”, sebuah panggilan lamda terdengar dari kamar depan. Suara
keseharian dari seorang perempuan yang umurnya terpaut tiga angka dibawahku.
Untuk menghindarinya aku lebih baik ke kamar membuka laptop dan melanjutkan
karangan yang telah kutulis sebelumnya saat di rumah. Karangan yang begitu tak
bermakna, penuh kata-kata basi diselimuti polusi. Tapi entah mengapa baru saat
ini aku menyadarinya. Ini mungkin cara alam bercerita betapa jarak bukanlah
halangan bagi sesuatu untuk bisa tetap dekat dan selalu bersama.
Menulis
merupakan rutinitasku setidaknya sekali dalam seminggu, seperti itulah
gambaranku saat ini. Sejak peristiwa itu, aku menjadi gemar menulis dan mulai gemar
membaca. Bagaimana bisa seorang yang bercita-cita ingin jadi penulis bisa
membuahkan karya tulis sedangkan untuk membaca saja ia sulit melakukannya.
Itulah pertanyaan yang mulai jadi kenyataan dalam diriku. Di mana pun seorang
penulis pasti dilahirkan dari seorang pembaca ulung, yang seakan bisa menyerap
kata-kata yang ia baca menyusunnya dan melahirkan kalimat yang akhirnya membuahkan
sebuah karya. Namun aku berbeda, keadaan yang membuatku begini. Ibuku gemar
membaca, dan setiap aku mendapat tugas menulis sejak SD ibuku pula yang selalu
menyusun kata-katanya. Layaknya mesin fotokopi aku hanyalah juru tulis yang
seakan mengalah oleh kenyataan. Bagaimana tidak, tulisanku memang buruk. Mengerti
baca tulis saja aku tertinggal dari teman-teman sebayaku waktu itu. Hal itulah
yang memaksaku untuk mengikuti pelajaran tambahan sepulang sekolah dengan wali
kelas dan anak lainnya yang bernasib sama, dimana jumlahnya tak lebih dari lima
anak.
Sampai
puncaknya saat aku menginjak bangku SMP kelas 2, guru bahasa Indonesia saat itu
menunjukku sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti seminar kepenulisan.
Banyak inspirasi yang kudapat, pembicaranya tentu tidak asing bagi mereka yang
gemar membaca sejak muda. Seperti salah satu pembicara yakni Boim Lebon, saat
itu ia memberi inspirasi mengenai penulisan judul, dan cara menyampaikan
kalimat-kalimat agar lebih bernilai. Seminar itu aku ikuti beberapa hari
sehingga aku tak masuk sekolah secara penuh. Bertempat di Balai Pusat Bahasa,
seminar itu memang sangat luar biasa dan aku merasa beruntung bisa mengikutinya
bersama seorang kakak kelas perempuan yang aku pun tak sempat bertanya namanya
meski sempat membentuk obrolan singkat beberapa kali dengannya. Sejak saat itu
pula aku mulai memutus segala bantuan ibu khususnya pada tugas mengarang.
Seperti mulai terbiasa dengan susunan kalimat yang padu yang biasa diberikan
ibu, aku mulai melangkah karena aku mulai sadar apa yang kulakukan merupakan
proses membaca tanpa sadar. Karena proses fotokopi yang selama ini aku alami
merupakan proses baca tulis.
Kegemaran membaca pun mulai muncul seiring kebutuhanku
akan kosakata dan inspirasi baru dalam menulis. Buku demi buku kubeli dengan
uang jajanku sendiri. Sebelum akhir pekan, sepulang sekolah merupakan jadwalku untuk pergi mencari
inspirasi baru. Tak jarang uang yang terbatas memaksaku untuk hanya mendapatkan
buku lama yang tertumpuk dengan kondisi penuh debu. Sampai akhirnya, keadaan
benar-benar telah melahirkanku kembali turun dari langit yang tak berwarna
menuju pantulan bias cahaya yang luar biasa indahnya.
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

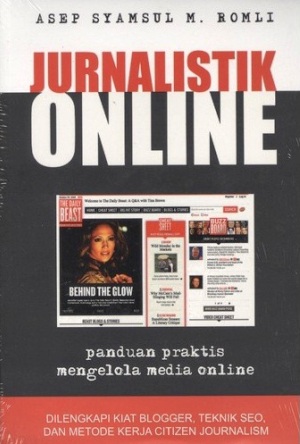

0 Comments for "Bukan Orang-Orangan Sawah - Madhika Ekatra - Lomba Menulis Cerpen"