NOSTALGIA
Oleh: Rose
Aku melangkahkan kaki memasuki SMA Gema Nusantara. Sudah hampir lima belas
tahun aku meninggalkan sekolah ini. Tugas negara membawaku kembali kemari. Tak
kupungkiri ada rasa rindu yang merayap didasar hatiku. Sekolah ini punya terlalu
banyak kenangan untuk kulupakan.
Tak kulihat ada perubahan di sekolah ini, kecuali fakta bahwa sekolah ini
sudah termakan usia, selain itu, semuanya masih sama seperti lima belas tahun
lalu. Warna bangunan yang didominasi warna putih, kini telah kusam, kulihat
dibeberapa bagian bangunan catnya sudah mengelupas. Gentengnya yang dulu
berwarna merah bata, kini telah ditumbuhi lumut. Pagarnya pun sudah berkarat.
Ingatan kembali berputar ke masa itu, lima belas tahun yang lalu. Saat itu,
aku adalah gadis polos yang penuh semangat dan keyakinan, impianku hanya satu,
menjadi seorang dokter. Aku masih ingat betul, ketika pak Susilo bertanya
kepada murid-murid tentang cita-citanya. Aku berdiri dengan percaya diri
mengatakan aku ingin menjadi dokter, tak kusangka, ucapanku menjadi lelucon
bagi murid lain. Ningsih, anak juragan terkaya di desaku, mengejekku, “Anak
buruh tani mana punya uang untuk sekolah kedokteran,” begitu katanya, seisi
kelas menertawaiku, wajahku merah padam. Pak Susilo hanya tersenyum kearahku
dan meminta murid-murid untuk tenang. Ucapan Ningsih begitu menusukku, dengan
amarah yang meluap-luap aku mendatangi dan menantangnya. Kukatakan padanya aku
akan menjadi lebih kaya dan lebih hebat dari bapaknya, perkataan yang membuatku
dihadiahi lemparan telur busuk dan tamparan di pipi kiriku.
Aku sebisa mungkin menahan tawa ketika mengingat betapa konyolnya aku yang
dulu. Entah kudapat darimana keberanian untuk menantang Ningsih. Ningsih anak
juragan, sedang aku hanyalah anak buruh tani rendahan. Waktu itu aku juga sama
sekali tak berpikir, akan hancur hidup keluargaku jika Ningsih mengadukan
perlakuanku pada bapaknya, bapaknya mungkin akan memecat orang tuaku. Aku
sungguh beruntung karena Ningsih tak mengadukanku, walaupun sampai sekarang aku
tak mengerti apa alasannya.
Semenjak kejadian itu, Ningsih selalu menggangguku, tak cukup hanya
menghinaku, bahkan dia dengan begitu berbaik hati memberiku julukan ‘gadis tak
tahu diri’. Julukan yang akhirnya dipakai seisi sekolah untuk memanggilku.
Lama-kelamaan Ningsih semakin keterlaluan. Dia, berkali-kali dengan sengaja
menarik kursi tempat dudukku atau melapisinya dengan lem. Hingga akhirnya
satu-satunya rok yang kupunya robek. Aku terpaksa memakai rok tambalan ke
sekolah.
Suatu hari, aku sudah sampai pada batas kesabaranku. Aku berkelahi dengan
Ningsih, itu pun karena dia yang memancingku duluan. Tentu saja Ningsih dapat
kukalahkan dengan mudah. Kemampuanku yang sudah terbiasa hidup keras dan
mandiri jelas tak sebanding dengan Ningsih yang hidup dengan bermanja-manja.
Kami berdua dipanggil ke ruang kepala sekolah, tapi bukan hidup namanya jika
keadilan dipegang teguh. Dalam situasi seperti ini, semboyan bahwa hukum ada
untuk dilanggar, sangat sesuai. Aku mendapat hukuman berat, setiap jam
istirahat aku harus menghormat bendera di lapangan yang terik, ditambah lagi
aku harus membersihkan WC sepulang sekolah. Sedangkan Ningsih? Jangan tanya,
dia bahkan diijinkan tidak masuk sekolah seminggu untuk menyembuhkan lukanya
yang tak seberapa.
Bukan gadis tak tahu diri namanya jika aku diam saja saat diperlakukan
tidak adil. Di lapangan upacara, aku slalu berteriak dengan keras, “ Ini tak
adil, sama sekali tak adil !”. Hanya itulah yang dapat kulakukan untuk melawan,
tapi, kurasa itu sia-sia saja, bahkan malah memperburuk keadaan. Aku mendapat
ancaman dari kepala sekolah, jika aku terus bertingkah, aku akan dikeluarkan.
Gemerisik daun yang tertiup angin menyadarkanku untuk kembali ke masa
sekarang. Pandanganku tertuju pada sebuah pohon beringin tua yang berdiri tegak
di ujung taman sekolah. Disanalah tempatku mengadu, menangis sepuas-puasnya,
mempertanyakan ketidakadilan yang kualami. Biasanya aku ditemani oleh Sari,
satu-satunya teman yang kupunya. Nasibnya tak lebih baik dariku. Sari anak
yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Ketika murid-murid lain menghabiskan
waktu istirahat dengan makan bakso dan bakwan goreng di kantin. Aku dan Sari
masih setia menyantap singkong rebus di bawah lindungan pohon beringin. Sari
adalah satu-satunya orang yang tak menertawakan cita-citaku. Alasannya
sederhana, kami memiliki cita-cita yang sama, menjadi dokter.
Aku duduk di bawah pohon beringin, menyandarkan punggungku ke batang pohon
yang sudah berkerut, pertanda usianya yang sudah tua. Kurasakan semilir angin
menerbangkan rambutku, membawa kesejukan. Sari, aku merindukannya, aku selalu
ingat kata-kata yang selalu diucapkannya untuk menyemangatiku, “Jangan menyerah
sekarang, kita harus terus berjuang, kita tak tahu apa yang ada didepan jika
menyerah sekarang.” Ah, meski sudah lima belas tahun berlalu rasanya baru
kemarin dia mengatakannya padaku. Setahun lalu aku bertemu lagi dengannya, dia
sekarang telah menjadi dokter, aku benar-benar kagum dengan perjuangannya. Dia
berhasil meraih mimpinya, tak sepertiku, yang menyerah di tengah jalan.
Sedangkan Ningsih, kudengar ia menikah tak lama setelah upacara kelulusan,
Ningsih hamil di luar nikah.
Handphone-ku berdering, sebuah pesan dari wakilku, Tika.
From : Tika
Maaf bu, ada wali siswa yang ingin bertemu ibu.
Tolong temui beliau, terimakasih.
Aku tersenyum membaca pesannya. Entah mengapa aku begitu bersemangat
menjalani tugas-tugasku, aku memang gagal menjadi dokter, tapi aku tak lagi
kecewa, aku mencintai pekerjaanku sekarang.
Kulihat seorang wanita seusiaku duduk di sudut sofa, penampilan memang jauh
berbeda dari yang dulu, tapi wajahnya tak pernah bisa kulupakan.
“Maaf ada yang bisa saya bantu?,” aku tersenyum lembut padanya.
“Bisakah saya meminta keringanan biaya anak saya?,” wajahnya memelas.
Untuk sesaat aku terdiam, terkejut mendengar permintaannya itu.
“Jangan khawatir, saya yang akan menanggung biayanya”
Bola matanya membesar, tatapan matanya seakan tak percaya dengan
perkataanku.
“Terimakasih,” ujarnya ragu, aku kembali tersenyum
“Sama-sama Ningsih”
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

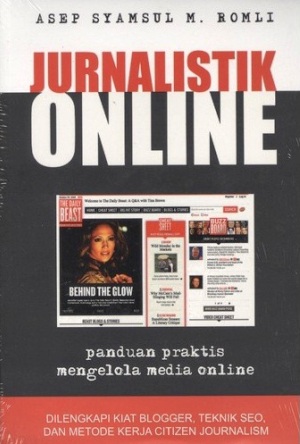

0 Comments for "NOSTALGIA - Rose - Lomba Menulis Cerpen"