Surat
Cinta dari Rumah Kedua
Fitri Wulandari
Semburat jingga
menemani ayunan langkahku di bawah lampion dunia yang mulai meredup senja ini.
Rasanya aku sudah tidak tahan dengan rasa pegal yang melanda kaki dan pundakku.
Ritual mengayuh sepeda dengan tas besar yang berisi tumpukan buku tebal di
punggung kecilku mungkin cukup untuk menjelaskan semuanya. Kupandang langit
senja di atasku, aku ingin terbang, aku ingin melepas penat yang sudah menjamur
dalam kehidupan yang membosankan ini. Jika aku ingin bunuh diri kira-kira apa
reaksi yang akan kuterima dari mereka semua, batinku mulai kacau. Toh mungkin
mereka tak akan memberiku reaksi apapun selain kata “jangan” yang mungkin malah
akan kuartikan sebagai “silahkan”.
Kupejamkan mataku,
merentangkan kedua tanganku seolah sebentar lagi aku akan terbang. Kegiatan ini
mungkin belum berhenti jika saja tidak
ada sebuah suara yang mengganggu kenikmatan ketenanganku ini.
“Mei! Sedang apa kamu,
ini sudah sore. Ayo!”, suara teduh itu menarikku keluar dari sepasang sayap
yang akan mengajakku terbang. Dan biarlah, aku menyukai senja jadi tidak ada
masalah bagiku. Dia memandangku, lekat. Mungkin baginya aku adalah seorang
makhluk aneh dari dunia lain yang saat ini tengah berdiri di hadapannya dengan
penampilan yang acak-acakkan.
“Aku mencintai senja,
Lila. Kau tidak usah khawatir”, aku menggerutu padanya. Namun, kenyataannya aku
tetap mengiyakan ajakan gadis hitam manis di depanku ini. Memasuki dunia
tempatku mengurung, asramaku, dunia yang di dalamnya banyak sekali pesaing
tangguh yang memiliki jutaan mimpi di benak masing-masing. Dan sekarang aku di
sini, berdiri di tempat ini. Tapi, aku tidak seperti mereka, aku tidak
mempunyai mimpi-mimpi itu ketika masuk dunia ini. Aku hanya lari dari apa yang
tidak kusenangi.
“Lagi-lagi kau melamun,
Mei. Ada apa denganmu?”,dan suara itu kembali mengangguku. Aku mendengus keras.
Kubuka pintu kamarku
dengan kasar diikuti Lila yang hanya bisa menatap nasib pintu itu, pasrah. Menghempaskan
tubuh penatku di atas kasur, kuedarkan
pandanganku mengelilingi ruangan sederhana ini. Bahkan ruangan ini tiga kali
lebih sempit dari kamarku, bagaimana bisa aku sudah menempatinya selama hampir
dua tahun. Baru saja hendak memasuki alam mimpi, suara seseorang
membangunkanku. Kupikir itu Lila karena jika benar itu dia aku akan dengan
senang hati memarahinya.
“Mei, ada tamu
untukmu”, itu suara Liza, tetangga kamar yang sangat menyebalkan dengan hobinya
yang suka mengganggu ketenangan orang lain.
Kukumpulkan kesadaranku
sebelum menemui “tamuku” tadi. Mencoba menebak siapa yang datang kubuka jendela
kamar, ah mereka lagi. Kenapa mereka selalu datang ke sini, melihat mereka
hanya akan membuat luka lama itu kembali ternganga.
“Mei, temuilah mereka.
Sudah beberapa bulan ini kau tidak menemui mereka setiap mereka datang menjengukmu”,
Lila yang baru datang mencoba membujukku.
“Aku tidak mau, Lila.
Apa untungnya jika aku bertemu mereka, tidak ada, kan?”, tanpa memandang Lila
ucapan yang cukup pahit itu meluncur dari bibir mungilku.
Lila terdiam mencoba
memahami makna dari ucapanku, aku menatap pada senja yang belum juga hilang.
“Mai,
ke sini. Ayah punya mainan baru untukmu”, ucap sosok itu sambil terseyum
bangga. Gadis kecil yang dipanggil Mai itu hanya tersenyum, lalu menyerahkan mainan
yang baru ia terima kepada Mei, sosok yang begitu lembut dan pendiam yang
sedari tadi berdiri di sampingnya. Ya, Mai dan Mei, dua saudara kembar yang
tidak akan pernah bisa dipisahkan.
Lelaki
yang dipanggil “ayah” oleh Mai tadi hanya memandang Mei iba, ya dia melupakan
sosok mungil yang satu ini. Namun, entah mengapa terselip sebuah benci di
hatinya. Kasar, ia merebut mainan yang dipegang olehnya, Mei hanya diam dengan
mata yang mulai berkaca-kaca, tangisnya pecah. Tidak ada orang yang meredakan
tangisnya di sana, tidak ada bunda yang akan memeluknya. Ayah bilang Meilah
yang telah membunuh bunda.
Lelaki
itu menggendong Mai dan meninggalkannya, sendiri di taman kecil itu. Mei hanya
bisa menangis berharap sosok bunda yang ia rindukan akan datang menemuinya.
Tapi, sosok itu tidak pernah datang. Mei: Aku membencimu, Ayah!
Saat itu usiaku sudah
delapan tahun, pantas jika sampai sekarang rasa sakit itu masih mengakar sebab
aku pun tidak memiliki keinginan utnuk menghapus memori menyakitkan itu.
Biarlah kenangan itu menjadi benang merah dalam hidupku yang tak berharga ini. Napasku
terasa berat, hingga tubuhku rasanya melayang, aku tak sadarkan diri.
“Mei, Mei..?”,
suara-suara bising itu berdengung di ujung telingaku. Aku ingat suara itu,
suara teduh bunda, bunda memanggilku, dia ada di sini. Sekarang aku melihatnya,
bunda memakai gaun yang begitu cantik dengan wajah yang bercahaya. Aku mencoba
mendekati bunda tapi, kenapa tidak sampai-sampai, rasanya lantai ini berjalan
mencoba memberiku jarak agar aku tidak bisa mencapai bunda.
“Mereka
menyayangimu, Mei.... Kembalilah...”,sayup suara bunda
tertangkap indra pendengaranku namun bunda semakin menjauh dari tempatku
berdiri, bayangan itu menjadi buram, aku berlari mengejarnya tapi bayangan itu
lebih dulu menghilang.
“Bunda!!!”, aku
tersentak disambut suasana lenggang dan suara jangkrik yang berpesta di tengah
gerimis malam. Kemana bunda? Kamarku masih dalam keadaan gelap, juga Lila yang
masih terlelap memeluk guling kesayangannya. Aku terisak, rasa rindu ini begitu
membuncah. Kulalui malam ini dengan bayangan bunda yang duduk di pelupuk
mataku.
“Mei! Bangun, Mei!
Cepat”, ah teriakan itu lagi. Aku mencoba untuk bangun dan meregangkan
otot-otot sendiku yang sedikit kaku. Membuka mataku perlahan, aku terbelalak.
“Ada apa, Lila? Wow!”,
kukerjapkan mataku beberapa kali untuk menyadari bahwa saat ini ada puluhan
balon warna-warni yang ada di depan mataku. Pintu kamarku terbuka, tapi kulihat
di luar gelap hingga...
“HAPPY BIRTHDAY TO MEI,
HAPPY BIRTHDAY TO MEI, HAPPY BIRTHDAY TO MEI!!!”, lagu itu terlantun begitu
indah dari teman-temanku. Hari ini tepat 13 Februari 2016, mereka merayakan
ulang tahunku yang aku sendiri selalu melupakannya. Air mataku tanpa izin sudah
mengalir melewati pipiku, bahkan ketika Liza, tetangga penggangguku membawakan
sebuah kue ulang tahun di hadapanku. Mereka punya cara untuk membuatku bahagia.
“Mei, kami punya sebuah
“Surat Cinta” untukmu. Pejamkan matamu dan dengarkanlah!”, ku pejamkan mataku,
menanti Lila membacakan “Surat Cinta” untukku.
Teruntuk
Meila Syahara
Mei,
ingatkah ketika pertama kita bertemu di tempat ini? Sebuah gedung tua yang
telah menyimpan ratusan cerita dan sekarang kisah kita abadi di dalamnya. Mei,
ketika itu kita berjanji akan menjadi sebuah keluarga. Ini kita Mei, kisah kita
yang sebentar lagi akan usai.
Air mataku kembali
turun, kelebatan peristiwa yang lalu kembali berloncatan di ingatanku.
Mei,
yang upik. Ingatkah ketika gumpalan tepung sagu dan telur serta air sabun itu
mengenai tubuh kita, moment yang sangat berbeda, bukan? Namun, ingatlah yang
lalu, si mungil yang terluka. Mei, lupakanlah masa sakit itu. Mereka
manyayangimu, ayah yang selalu menatapmu kala kau telelap, saudara yang selalu
memandang fotomu, menanggung rindu. Mei, mereka tetap di belakangmu. Mei, Mei
yang upik, Mei itu milik kami.
Tangisku pecah, lilin
sudah menyala. Bergetar aku meniupnya dengan berbagai harapan baru di hatiku.
Kami saling berpelukan, mereka teman-temanku, keluarga dari rumah keduaku. Yang
memiliki cara berbeda untuk membuatku tertawa.
“Mei?”, suara berat itu.
Aku menolehkan kepala, mereka di sini.
“A...Ayah? Mai?”, aku
menghambur. Memeluk keduanya, pelukan ini terasa begitu erat seolah aku akan berlari
jauh jika mereka melepasnya. Bunda, aku kembali. Aku melihat bunda tersenyum di
ujung mataku.
Aku memandang
wajah-wajah yang telah menemaniku selama dua tahun terakhir ini. Inilah
keluargaku, yang menyayangiku dengan cara yang istimewa, keluarga kedua yang luar
biasa, yang memberiku sepucuk surat cinta dari rumah keduaku, asrama tercinta.
Keluarga hebat yang menyadarkanku agar kembali menyadari kasih sayang dari
keluargaku yang sebenarnya, sebuah keluarga yang lebih dari indah.
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

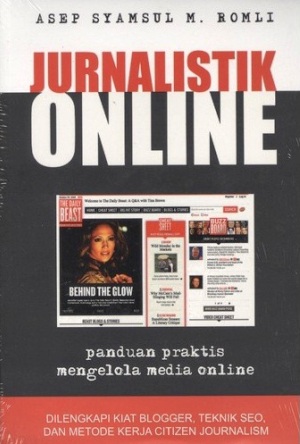

0 Comments for "Surat Cinta dari Rumah Kedua - Fitri Wulandari - Lomba Menulis Cerpen"