Hujan,
Senja dan Kita
Ulva
Afdillah Umar
Gerimis turun perlahan. Menyapu tiap
rindu dengan rinainya yang sendu. Gemericik air yang turun membuat nada sendu
di ujung telinga. Di tepi jalan sana, orang-orang setengah berlari menghindari
rintik air yang kian lebat. Melindungi kepala dari terpaan air hujan. Pakaian
yang basah nampaknya menyiratkan gundah di hati mereka.
Senja mulai menampakkan biasnya
dengan malu-malu. Kemilau cahyanya terhalau oleh rintik hujan. Membuat suasana
menjadi semakin sendu. Kulangkahkan kaki dengan begitu ringan, tak peduli
terpaan air yang membasahi wajah dan rambut. Tak peduli tatapan aneh dari
mereka yang menghindar dari dingin dan gigilnya air hujan. ”Ini hanya air, bukan? Kau takkan terluka
olehnya.” Gumamku dengan gurat senyum tipis.
“Hei … Apa yang kau lakukan di
sana?” tegur seseorang dari balik kaca mobil yang hitam. Aku menoleh, kutatap
lamat kaca mobil yang masih tertutup itu. Seketika itu pula si pemilik
menurunkan kaca mobilnya.
“Ifat?” ucapku setengah kaget. Aku
melangkah lebih dekat, kutatap dengan seksama wajah lelaki yang kini semakin
dewasa. Aku menyeka ujung mata yang kini berair. Dia selalu saja seperti itu.
Tak berubah sedikit pun. Tak pernah memberiku kabar jika ingin datang ataupun
pergi. Bahkan ia selalu tahu tempat yang sering aku sambangi saat senja mulai
menyapa dengan warna merah saganya.
“Masuklah. Hujan semakin deras. Kau
bisa sakit.” Tuturnya dengan senyum khas yang selalu kurindukan. Sahabat
terbaik yang pernah kutemui. Sahabat kecil yang selalu menjagaku layaknya seorang
kakak. Aku mengangguk sembari melangkah memasuki mobil mewah yang warnanya kian
pudar.
***
Senja semakin nampak dengan rinai
hujan yang kian redah. Ifat mengarahkan mobilnya menyusuri tempat terujung dari
kampung halaman kami. Tempat yang selalu kami sambangi saat masih kanak-kanak
dulu. Tempat yang kami jadikan sebagai saksi akan mimpi dan cita-cita yang
menggantung setinggi langit. Tempat yang kami sebut sebagai pulau senja.
Ia tak berbicara sedikit pun.
Layaknya aku yang memilih diam jika tak ditanya olehnya. Sesekali aku melirik
ke arah Ifat. Raut wajahnya dipenuhi gurat kelelahan akibat kesibukan yang kian
memuncak. Tahun ini adalah tahun-tahun tersibuk Ifat sebelum memasuki dunia
kerja yang terkenal kejam. Tahun-tahun terakhir yang ia habiskan untuk menyusun
skripsi dan ujian akhir. Mungkin itu juga alasannya mengapa ia tak sehangat
dulu. Sibuk dengan tumpukan buku yang siap untuk dibaca.
Aku menghembuskan nafas berat.
Mengontrol pikiran yang tak tentu lagi arahnya.
”Rinai.” Ucap Ifat datar. Aku
menoleh dengan dahi berkerut. Menunggu kelanjutan dari ucapan Ifat yang terasa
menggantung bagiku. Pandangannya terus mengarah ke depan. Tak sedikit pun
menghiraukan aku yang menunggu ucapan selanjutnya.
“Wisuda semakin dekat. Aku telah
meraih gelar yang sangat diharapkan ayah dulu. Namun sekarang, seperti yang kau
ketahui ayah telah tiada. Dan ibu pun semakin renta. Itu berarti semua ini
membuatku harus berpikir keras untuk kelanjutan usianya. Kau tahu, kan? Aku
pernah berjanji pada ayah bahwa aku akan membahagiakan ibu di sisa-sisa
hidupnya dan sekarang aku berusaha untuk memenuhi setiap janji yang kutanamkan
di setiap sudut liang lahat ayah.” Kata Ifat dengan suara bergetar. Kusentuh
tangan Ifat yang nampak jelas urat-uratnya. Itulah caraku menenangkan hatinya
jika sedang kacau. Aku tak berani berkata apa-apa. Kubiarkan ia menyelesaikan
setiap kata yang memenuhi ruang otaknya. Kata yang (mungkin) selama ini ia
pendam dari siapapun. ”Setelah acara wisuda nanti, aku akan ke Jerman. Aku akan
melanjutkan studi di sana. Aku juga ditawari sebuah pekerjaan oleh sahabat ayah
yang bermukim di Jerman. Dan itu berarti ruang pertemuan kita akan semakin
sempit.” Ucap Ifat dengan wajah tertunduk.
Mobil yang kutumpangi berhenti di tepi pantai yang
berombak. Perkataan Ifat terngiang di telinga hingga menembus syaraf otak.
Membuat sesak di dalam dada hingga ketakutan akan kemungkinan-kemungkinan yang
selama ini kutepis tiba-tiba bertumpuk dan berlalu lalang dalam kepala. Sebisa
mungkin kuatur nafas yang kian berat. Kutengadahkan kepala agar air yang
menghiasi pelupuk mata tak tumpah ruah. “Jangan
menangis Rinai.” Batinku. Aku tak ingin Ifat tahu jika aku bersedih akan
kepergiannya yang menghitung hari.
“Lalu apa yang kau pikirkan? Bukankah itu salah satu
jalan untuk membuat ayah bangga dan ibu bahagia di akhir usianya?” ucapku
dengan raut wajah yang menipu. Ifat menoleh dengan gurat kesedihan yang nampak
jelas. Sekali lagi aku menyunggingkan senyum terpaksa ke arah Ifat lalu
memalingkan wajah dengan segera.
“Maafkan aku Rinai. Aku belum bisa menepati janji
ayahmu untuk terus menjaga anak perempuannya.” Ujar Ifat lagi sambil menyeka
ujung matanya yang berair. Aku tak berani menoleh ke arah Ifat. Aku hanya
mengangguk kecil sembari memalingkan wajah ke luar. Kutatap senja yang kini
semakin menghilang. 47 detik yang takkan kulupakan. Di bawah rona merah langit
sore, pertemuan yang kemudian membuat hari-hariku berubah dari biasanya. “Ifat … “ Batinku.
***
Dua bulan setelah kejadian di tepi
pantai favorit aku dan Ifat, aku mendengar kabar jika ia telah melangsungkan
wisuda yang hanya dihadiri oleh ibu dan sanak keluarganya. Tak ada undangan
untukku. Tak ada ucapan basa-basi untuk mengajakku ke acara penting itu. Bahkan
ibu pun menanyakan perihal wisuda Ifat yang tak dihadiri olehku. Sebagai orang
yang mengetahui kedekatan kami sejak kecil, wajar saja bagiku jika ibu
berpikiran negatif tentang hubungan kami. Namun aku menepis setiap kekhawatiran
yang tersirat di dalam hati ibu.
“Kami baik-baik saja, bu.” Kataku di
suatu pagi saat membantunya menyiapkan sarapan. “Mungkin dia sibuk hingga
akhirnya lupa untuk mengajakku ke acara wisuda itu.” Ucapku meyakinkan beliau.
Beliau hanya bergumam kecil. Aku mendekap erat tubuhnya dari belakang. Berusaha
menepis setiap kekhawatirannya akhir-akhir ini. Ibu membalikkan badan lalu
membelai lembut rambutku yang tergerai kusut. Beliau tersenyum. Keriput di
ujung mata beliau menandakan jika ia tak lagi semuda dulu. Cobaan hidup yang
kami alami saat kepergian ayah membuatnya harus bekerja keras demi memenuhi
pendidikanku. Dan saat-saat seperti inilah aku selalu merindukan sosok ayah.
Sosok lelaki yang tak henti-hentinya mencurahkan seluruh kasih sayangnya
padaku. Lelaki yang tak pernah membiarkan anak perempuannya meneteskan air
mata. Aku menarik nafas berat. Kuseka ujung mata yang lagi-lagi mengerti akan
rasa yang ada di dalam hati. Kudekap ibu lebih erat. Berharap pelukannya dapat
meredakan setiap kegelisahanku akan Ifat. “Ayah,
aku merindukanmu. Maafkan Ifat, ayah. Ia tak bisa menepati janjinya”
Gumamku dalam hati.
***
Hujan kembali menyapaku hari ini.
Hari di mana Ifat akan segera pergi. Hari di mana Ifat akan menjalani kehidupan
barunya di negara orang. Hari di mana Ifat akan menyibukkan diri dengan segala
rutinitas di Jerman hingga membuat memori otaknya yang dulu menyimpan ribuan
kenangan bersamaku berkurang secara perlahan.
Jam telah menunjukkan pukul 09:00
pagi. Namun matahari belum juga nampak dari ufuk timur. Sinarnya tertutupi oleh
awan mendung. Semendung dan sedingin hatiku saat ini. Semalam Ifat berjanji
akan mengunjungiku sebelum ia berangkat ke Jerman. Namun cuaca sepertinya tak
mendukung pertemuan kami. “Biarlah …
biarlah jika ia ingin pergi tanpa memberitahuku. Toh, aku sudah bisa menerima
semua itu dengan lapang dada. Apa bedanya jika ia memberitahuku atau tidak?
Pada dasarnya semua sama, kan? Ia tetap akan pergi untuk waktu yang lama.
Membiarkanku sendiri dengan perasaan yang tak pernah terungkap sebelumnya.” Ucapku
dalam hati. Aku memilih menikmati rinai hujan dari dalam kamar. Merasakan
setiap gemericik air yang tumpah menghujam tanah. Menunggu hingga letih
kehadiran Ifat menjemputku bersama duka kepergiannya.
15 menit berlalu. Nada dering
teleponku terdengar samar. Aku bergegas meraih telepon genggamku yang terselip
di bawah bantal. Sebuah pesan muncul di atas layar. Aku bergegas membukanya. “Ifat … “ ucapku lirih. Itu pesan dari
Ifat. Entah apa isi dari pesan tersebut. Ribuan pertanyaan tiba-tiba muncul
dalam kepala. Gugup dan rasa khawatir kemudian bercampur menjadi satu. Seketika
itu pula, pikiran-pikiran negatif kembali muncul.
”Hai
Rinai. Apa kau sudah bangun? Hari ini hujan menyapamu lagi, bukan? Sejak tadi
ia datang menghampirimu. Apa kau sudah melihatnya? Cuaca pun sedang sangat
dingin. Semoga tak sedingin hatimu saat pertama kali kita bertemu di pulau
senja. Maafkan aku, Rinai. Jadwal keberangkatanku di majukan lebih awal. Pagi
tadi aku buru-buru ke bandara, tak ingin ketinggalan pesawat hingga akhirnya
aku lupa jika aku harus menemuimu sebelum pergi. Semoga ini tak membuatmu kesal.
Semoga ini tak membuatmu seperti Rinai kecil yang dulunya jika ditinggal pergi,
ia akan meronta sejadi-jadinya. Aku pasti kembali untuk menemuimu. Dan saat aku
datang lagi, kita akan tetap seperti dulu. Menikmati senja di bibir pantai
dengan deru ombak sebagai nyanyiannya. Kau sahabatku, kan? Kau menyayangiku,
kan? Itu artinya kau tak boleh marah padaku. Semua ini demi ibu, Rinai. Andai
bukan karena beliau, aku tak mungkin meninggalkanmu. Tetap bahagia dan tetaplah
menjadi sahabatku. Maaf karena aku tak bisa menemuimu sebelum pergi. Ifat …
Sekali lagi dia pergi
tanpa menemuiku. Untuk kesekian kalinya pula aku hanya dianggap sebagai sahabat
oleh Ifat. Sudah kuduga, ia takkan datang. Sudah kuduga, ia akan mengingkari
janjinya. Aku menengadahkan wajah, menatap langit-langit kamar yang biru.
Mungkin dia memang tak perlu tahu tentang rasa ini. Tentang rasa yang kusimpan
rapat sejak 8 tahun silam. Tentang rasa yang tak pernah ia pahami dan tentang
rasa yang tak pernah ia miliki seperti aku yang memilikinya.
“Kau
benar, Fat. Selamanya kita akan tetap menjadi sahabat. Selamanya hubungan kita
akan seperti ini. Tidak lebih namun takkan berkurang. Mungkin memang hanya aku
yang mencintaimu lebih dari sahabat. Mungkin memang hanya aku yang menginginkan
hubungan ini tanpa batas. Dan mungkin memang hanya aku yang bodoh. Mencintaimu
lebih dari batas wajar. Tak apa, Fat. Harusnya aku memang tak berharap lebih
dari hubungan kita. Takkan kubiarkan rasa ini mengusik tidurmu. Takkan
kubiarkan kau mengetahuinya sampai kapanpun. Biar hujan, senja dan aku yang
tahu. Seberapa sering aku menyebut namamu di hadapan mereka. Biar hujan dan
senja yang menjadi saksi tentang hubungan kita yang takkan melebihi apa-apa.” Batinku
dengan mata sembap.
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

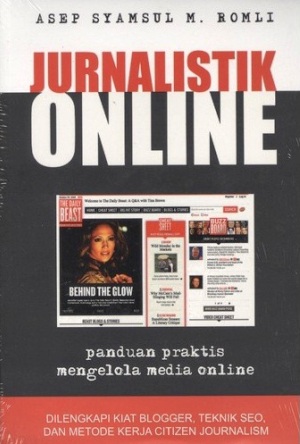

0 Comments for "Hujan, Senja dan Kita - Ulva Afdillah Umar - Lomba Menulis Cerpen"