SURTINI
Oleh:
Anung D’Lizta
“Masa laluku kelam, apa engkau tidak menyesal mau
menikahiku?”
“Tidak, karena aku ingin menjadi
bagian dari masa lalumu, agar sakitmu tidak seperti bisul. Yang bila pecah, kamu
merasakan sakitnya sendirian.”
Sekarang kerinduannya
bagaikan padi di sawah. Terus menerus diserang rumput dan hama menggerogoti
tiap benih yang hendak tumbuh. Meski seupaya daya akar dan batangnya kokoh
berdiri. Hanyalah kekosongan yang dihasilkan. Begitu juga dengan jiwa raganya.
Kosong tak terisi oleh canda tawa layaknya impian tua.
Pecutan
rindu pada usia mudanya tak sekuat usianya kini. Rambut di kepalanya hampir
seluruhnya dipenuhi uban. Setiap sudut wajahnya dipolesi keriputan. Nanar
matanya menatap langit berwarna gulita. Kesunyiannya bagaikan senar-senar yang
mengikat langkah kakinya.
Sekian
tahun berlalu. Dari pernikahan yang gersang. Tak ada air sungai mengalir
memberikan kesejukan lahir dan batiniyah. Tatapannya pada hamparan padi yang
menguning hambar. Kehampaan melilit sekujur sisa-sisa tuanya. Walau bertemankan
sosok lelaki setia, tak mampu mengobati kerinduannya pada wajah bersih polos tanpa
dosa. Kehadiran seorang anaklah yang ia dambakan.
“Meski
kita menua tanpa buah cinta, aku akan selalu setia menemanimu.”
“Suamiku,
apakah engkau tak merasa kesepian?”
“Sungguh
aku sangat kesepian. Maka janganlah berpaling meninggalkanku.”
Mujur
bagi wanita yang bernama Surtini itu. Ia memiliki suami, selain penyayang juga
setia. Cerita kenakalan Surtini di Hongkong semasa masih TKW tak membalikkan
niat Irham, suaminya untuk berpaling ke wanita lain. Cintanya pada Surtini
begitu kental, hingga kedua telinganya ia tutup rapat-rapat dari bisikan para
tetangga. Cerita miring apa pun tentang Surtini, Irham memilih buta dan tuli.
Ia tak peduli sama sekali. Surtini hanyalah korban, keyakinan itu kokoh dalam
relung hatinya. Pondasi cintanya terbukti kuat hingga sekarang.
“Surtini,
di Hongkong sudah bolak-balik aborsi.”
“Iyah,
hamil sama pacaranya, dan gonta-ganti lanangan.”
Begitulah
kira-kira bisikan dan godaan para tetangga yang berseliweran jika Irham
melintas di hadapan mereka. Pun demikian benih cinta di dada Irham, laksana
lentera yang siap menerangi Surtini. Tak akan redup walau angin puyuh beliung
datang.
Malam
telah melintas. Tergambar bayang-bayang bocah kecil dalam benak Surtini. Dalam
tidurnya ia sering memimpikan janin-janin bayi yang dulu ia gugurkan. Dengan
bantuan obat-obatan, entah berupa ramuan yang ia racik sendiri dengan ilmu
kengawurannya atau membeli pil perontok janin di toko China.
Bagi
Surtini tidak terlalu sulit melakukan semua itu. Apalagi di negara yang
memiliki mitos memakan janin dapat menguatkan stamina kejantanan pria. Pada
Along, sang pemilik toko, Surtini sering diiming-imingi lembaran dollar, jika
mau memberikan guguran janinnya. Karena terdesak oleh rasa ‘ingin bekerja’ dan
aib keluarga, maka dengan gampangnya Surtini mengikuti tawaran setan.
Kehidupan
masa lalu Surtini tak sekelam sekarang. Saat di Hongkong, ia sering dilempar ke
satu buaya ke buaya lain. Yang sama-sama jantan, jika ia mengerang maka
tubuhnya akan penuh dengan pukulan. Surtini kerap disiksa oleh majikan yang
pecundang. Surtini mencoba kabur, ia ditolong oleh Singa jantan. Perlakuan
menyakitkan pun dialami oleh Surtini. Bagaikan sistem barter, tubuh Surtini
kerap dijadikan sajian di meja judi. Jika pacar Surtini kalah, maka sebagai
jaminannya Surtini harus digilir lelaki bejat.
Nyeri,
amis, dan trauma membayangi tempurung kepala Surtini. Ia malu untuk
menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Malu atas nasib yang menimpa pada
dirinya. Hendak menyalahkan Sang Agung, rasanya ia juga terlalu bodoh. Andaikan
saja, Surtini menggunakan akal sehatnya pasti penganiayaan yang dialaminya
tidak berlarut panjang.
“Ya
Allah Mba, mending kabur saja ke KJRI, daripada disiksa majikan begini.”
Begitulah saran dari setiap teman sesama TKW bila melihat Surtini di pasar.
“Saya
takut di blacklist Mba, saya juga butuh uang untuk keluarga.” Dengan dalil
‘butuh uang’ maka Surtini memilih resiko disakiti. Bukannya mencari
perlinduangan ia malah asik menahan sakitnya.
Matanya
mengeluarkan airmata dalam tidurnya. Kekeringan benar-benar melanda masa
tuanya. Bantal lapuk dan dekapan suami menjadi kasur kehangatan setiap
malam-malamnya. Walau ia rasakan kadang kurang cukup menghangatkan kegigilan
relung jiwanya yang kering kelontang.
“Apa
yang kamu tangisi lagi, Dik?” panggilan sayang masih menyala. Bibir Surtini bergerak,
seakan ingin berbicara namun sekat pisau menusuk dua ujung bibirnya hingga ia
tak mampu mengeluarkan kata-kata. Hanya rasa sakit yang kian mendalam, sampai
ia sesunggukkan.
“Apakah,
aku tidak bisa membuatmu bahagia?”
“Bukan
begitu suamiku.”
“Lantas
apa yang membuatmu menangis?”
“Aku
hanya merasa rindu. Rindu pada tangis anak kecil.”
“Bersabarlah,
sekarang bersihkan pikiranmu dari rasa bersalahmu dan serahkan semuanya pada
Yang di Atas.”
Petuah
suaminya, hanya berlaku sesaat. Kala kerinduan mencabik, Surtini pasti akan
meringsek dalam dekap salah yang berlarut panjang.
~**~
Getah
yang mengering, ia tak akan mudah encer kembali. Begitu pula dengan sebuah
penyesalan bila sampai ke ulu hati terdalam. Pagi itu, Irham berencana
memanjakan Surtini dengan opor ayam bikinannya. Tidak susah mendapatkan
bumbu-bumbunya. Ayam, tinggal ambil satu di peternakan kecilnya, sedangkan
rempah-rempah, ada yang tumbuh di pelatar rumahnya.
“Mas
…”
Meski
sudah kakek dan nenek, Irham dan Surtini masih memanggil dengan panggilan muda.
Surtini memanggil suaminya, tidak ada sahutan. Ia memanggil suaminya sekali
lagi, “Mas …” masih juga tak ada sahutan.
Surtini
penasaran, mengapa suaminya tidak menyahut. Ia melongok ke belakang rumah.
Irham sedang memotong leher ayam betina. Surtini tercekat, kakinya gemetar
serta bola matanya mulai berair. Rasa sakit menyerang hatinya, jantungnya turut
merasakan imbas dari kesakitan hatinya. Denyutnya berdetak kencang. Surtini
semakin gemetaran melihat darah yang menetes dari leher ayam.
Surtini
meronta, ia kembali pada masa lalunya. Kesakitan itu yang berakibat, tidak
mungkin lagi bagi Surtini untuk hamil.
“Push
… push … harder!” seru dokter yang memaksa Surtini menguat lebih keras lagi
untuk mengeluarkan sisa-sisa janin dalam rahimnya. Meski, sudah melihat Surtini
kehabisan tenaga, dokter itu masih memaksa Surtini.
“Dik
… kamu kenapa?” Irham bergegas memapah tubuh Surtini yang kurus kering.
“Da-ra-h
…”
Irham
paham akan maksud istrinya. Ketakutan Surtini kambuh kembali. Bila melihat
darah, ingatan Surtini bagaikan peluru yang membidik-bidik jantungnya hingga
bunyi dentuman kuat siap merobohkan bahkan mematikan jiwanya.
Irham
membaringkan Surtini di kursi kayu panjang, ia meladeni istrinya dengan
pelayanan kelas atas. Diusapnya kening Surtini dan dibelai-belai layaknya anak
kecil.
“Apakah
engkau tidak bosan denganku, Mas?”
“Sampai
ajal memisahkan pun, aku akan tetap menjadi suamimu.”
Bibir
Surtini mengembang, gambar bahagia tergurat di setiap ujung bibirnya yang
tertarik oleh senyum tulusnya. Surtini mencium punggung tangan suaminya. Saat
kata SAH dari para saksi, saat itulah Surtini menemukan malaikat dalam
hidupnya. Rasa sunyi di hari-hari senjanya tidak seseram yang ia bayangkan.
~**~
Rinai
hujan bermain irama sore hari. Saat cakrawala menumpahkan gugusan gelap.
Sesekali petir berburu lirih. Bagai kilatan kembang api, memainkan kerinduan
pada semesta. Padi-padi di sawah bergoyang. Meski dingin tanpa selimut
kandi-kandi yang digelar oleh petani.
“Mas,
kapan kita panen lagi?”
“Mungkin
minggu depan, Dik, kenapa?”
“Rasanya
aku ingin memetik padi-padi kita di sawah.”
“Sebaiknya
kamu di rumah saja, menyiapkan makan dan minumku. Urusan sawah biarlah aku yang
mengerjakan.”
“Engkau
selalu melarangku menceburkan kaki ke lumpur, kenapa?”
“Karena
aku sayang padamu, dan tidak ingin kamu capek.”
“Bukankah
hidup itu sudah capek, suamiku. Lalu kenapa harus takut?”
“Sekarang
makan dulu opor ayam bikinanku. Pasti lezat sekali.”
“Tentu
aku percaya, suamiku memang pandai memasak.”
Surtini
menuruti ucapan suaminya. Nasi yang masih mengepul kukus dan opor ayam baru
diangkat dari wajan. Di rumah tua mereka berdua. Begitu setiap harinya. “Andaikan kita punya anak …”
Irham
tidak menggubris ucapan Surtini. Beruntunglah Surtini memiliki suami yang tingkat
kesabarannya begitu luas tak berporsi. Meski kadang ada jenuh di lubuk hati
Irham bila istrinya menyebut anak dalam suasana berdua. Dan memang mereka sudah
terbiasa berdua. Kehadiran anak bukan tujuan nomor satu menikahi Surtini.
Andaikan saja cinta Irham tak begitu tulus kepada Surtini, ia pasti sudah lama
meninggalkan wanita tua yang tak bisa hamil lagi sejak lama.
Kembang
jambu air berguguran ke tanah. Sudah musimnya panen jambu. Biasanya anak-anak
tetangga menjadi obat kerinduan Surtini dan Irham. Walau ingin mendekap—ada
keraguan dalam hati Surtini.
“Mbah,
minta jambunya yah …”
“Ambillah,
petik pakai genter,”
“Iyah
Mba, suwun.”
Lalu
Surtini akan duduk di kursi depan rumah menyaksikan anak-anak memetik jambu
air. Ada yang memanjat ada pula yang memetik memakai genter. Sudut bibir
Surtini akan mengembang bahagia. Lalu Irham akan menemani duduk di sampingnya.
Senja
membuka tabir indah. Dekapan Irham ke pundak Surtini bukan kepalsuan. Demi Dzat
yang memberikan rasa cinta, begitu juga Irham menjaga cintanya sebaik mungkin.
Kepala mereka telah sama-sama ditumbuhi uban namun rasa jenuh dalam pernikahan
jauh dari tempurung otak kepala mereka. Terlebih Irham yang menjadi lentera
buat Surtini. Ia tak akan padam cahayanya. Meski sekelibat pendar membayang
dalam cekam kesendirian.
Bila
berdua memangku kasih, anak-anak sering tersenyum memperhatikan Surtini dan
Irham. Mungkin di nalar otak kecil mereka berkata, “Sudah tua tapi romantis.”
Lalu apa yang bisa digambarkan oleh Surtini dan Irham, selain ketulusan cinta
mereka. Seperti lidah Surtini berucap beberapa tahun lalu.
Jika musim padi
telah datang
Sambutlah dengan
keriangan
Dengan senyum
mengembang
Di bawah
teriknya surya ada kedahagaan
Maka engkau
hadiahkan sekuntum senyuman
Sebagai penyegar
kekeringan kasih sayang
~**~
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

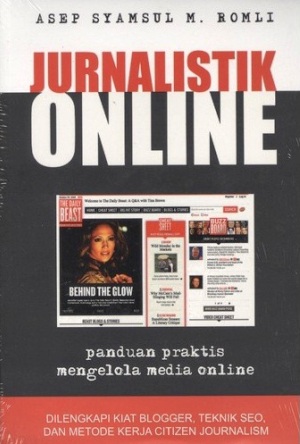

0 Comments for "SURTINI - Anung D’Lizta - Lomba Menulis Cerpen"