Dekat
Oleh: Heni Kusuma
Hujannya
pertama bulan November, setelah sekian lama dinanti, setelah rerumputan kering,
setelah hutan terbakar, setelah mata air surut dan setelah-setelah lain yang
membuat kami harus sholat istisqo’ di sana sini. Tak henti-henti kami mengucap
syukur, melihat sekeliling menghijau asri. Balut-balut kabut menenteramkan
hati, hujan telah kembali.
“Sudah
jam empat, Mas Rosyid”, seru Pak Amir, penghuni rumah terdekat masjid
Al-Hidayah. Hampir satu jam sejak sholat ashar berjamaah, Pak Amir dan aku
masih setia bersila di atas karpet hijau masjid. Jamaah sholat ashar hari ini
hanya lima orang. Aku, pasangan suami istri berumur 70 tahunan yang masih
bersaudara dengan pak Amir, istri Pak Amir, dan Pak Amir sendiri. Tak heran,
hujan mengguyur sejak ba’da dhuhur. Sangat lebat dan tak kunjung berhenti. Maka
dari itu Pak Amir sengaja tinggal untuk menemaniku barang membaca Al-Quran satu
juz.
Kami
keluar menuju teras masjid. Seperti tak ada tanda-tanda hujan akan mereda,
apalagi berhenti. Ember penampungan di bawah talang air di sisi kanan masjid,
dimana genteng rumah Pak Amir dan genteng Masjid bertemu, sudah tak mampu lagi
memberi ruang bagi curahan air. Berdiri tak banyak bicara. Kami hanya menatap
bulir-bulir itu yang dengan tegasnya jatuh menimpa dan mengalir ke penjuru
manapun yang mereka mau.
“Sepertinya
mereka tidak datang, Pak Amir”, aku menengok arloji yang melingkar di
pergelangan tangan kiriku. Sepuluh menit lewat dari jam empat. Aku menatap
papan hitam kelabu yang tertulis beberapa doa sehari-hari. Terlihat sisi kiri
papan itu tersabik air tampuan hujan yang terpias halus dari atas.
Bercak-bercak basah melunturkan goresan kapur tulis.
“Sayang
ya, rumah mereka jauh dari masjid. Orang tua mereka pasti juga banyak yang
belum pulang kerja. Tidak ada yang mengantar”, pak Amir mengusap wajahnya. Air
hujan juga tertampu di wajah beliau yang kian keriput. Aku tersenyum, dan
kembali menatap hujan.
“Apa ya
saya perlu mendatangi rumah mereka satu-satu? hahaha”, kataku sambil terus
menerawang selimut kabut di udara. Pak Amir tertawa, lalu memandangku.
“Sampean
ini semangat sekali. Alhamdulillah, padahal baru tiga bulan bertugas.
Sebelum-sebelumnya, bulan tiga itu mereka masih belum bisa kerasan lho, Mas.
Sayangnya…. nggak ada prawan di sini. Kalau ada, pasti sampean sudah saya
rekomendasikan. Hahahaha….”, aku terhenyak dan ikut tertawa.
“Mas
Rosyid, kalau saya balik duluan bagaimana? Saya mau mengurus itu, anu, buat
penyambutan KKN minggu depan. Besok juga masih ada rapat di balai desa”, Pak
Amir membuka payungnya. Hadiah undian sepeda sehat dua bulan lalu, dari
sponsor.
“Oh,
monggo, monggo, Pak. Alhamdulillah jaza kallahu khoiroo sudah menemani saya.
Maaf malah mengganggu pekerjaan, Bapak”. Pak Amir tertawa renyah sesaat sebelum
mengenakan sandalnya.
“Sampean
istirahat aja, Mas. Paling-paling mereka juga nggak datang wong masih deres
begini hujannya. Libur dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum!”
“Iya,
Pak. Wa’alaikumsalam”, Pak Amir setengah berlari dan hilang dibalik daun pintu.
Aku masuk ke kamarku yang ada di bagian belakang masjid. Sebuah ruangan
berukuran 3 x 3 meter yang memang sengaja disediakan untuk orang-orang
sepertiku. Tidak terlalu luas, tapi sudah lebih dari cukup untuk menampung
barang-barangku. Aku
hanya butuh lemari kecil. Di atas lemari itu bisa kugunakan untuk menaruh
buku-buku dan kitab. Juga meja untuk tulis-menulis atau sekedar menopang dagu
sambil melamunkan keluarga di rumah. Serta sebuah dipan untuk membaringkan
tubuh usai mengajar ngaji.
Mas
mubaligh atau mas ustadz, begitu orang-orang desa ini menyebutku. Setelah
setahun lebih menggali ilmu agama di pondok pesantren, kini aku diamanahkan
untuk menyampaikannya kepada orang-orang. Bahasa kasarnya, aku dilepas di
daerah yang bahkan mungkin tak pernah kucari dalam peta Indonesia. Aku dipertemukan dengan masyarakat baru,
kebudayaan baru, kebiasaan baru, dan aku harus membantu memperbaiki serta
memantapkan kepercayaan mereka akan Islam yang murni berbekal ilmu yang telah
kumiliki.
Hujan
memang belum ingin berhenti. Aku membenamkan diri dalam selimut. Sesungguhnya
aku sangat lelah. Sejak pagi aku sudah ikut Pak Amir bekerja bakti di kampung
sebelah. Selepas itu aku masih harus membantu mengepel lantai masjid dan
membersihkan jelaga di atap-atapnya. Bulan depan aku juga harus siap dengan laporan
rekapitulasi nilai anak-anak TPA. Semalam tadi ada pengajian umum hingga pukul
23.00. Aku mengantuk. Sejenak
aku terbayang keluarga di Lampung. Kelihatannya saja aku baik, rindu mendalam
itu tetaplah ada. Bulan-bulan pertama di pondok pesantren, di kota Kediri,
rasanya memang ingin segera lulus dan pulang. Kontras budaya dan semua hal yang
benar-benar baru membuat hari-hariku kian tertekan. Tetapi, sejak awal, menjadi
diriku saat ini adalah mimpi. Sehingga pilu itu tidak selamanya ada. Aku
sekarang bahkan sangat menikmati.
***
“Mas,
nanti malam ada penyambutan sekaligus acara sosialisasi dari KKN. Mas Rosyid
dapat undangan nih. Nanti berangkatnya bareng saya, di rumah Pak Andi”, Pak
Amir menemuiku ba’da dhuhur. Aku menerima selembar surat undangan, masih rapi
dengan klip menahan lipatannya.
“Mahasiswa
UNY?” aku mengintip.
“Iya,
KKN-nya mahasiswa UNY. Universitas bagus itu, Mas. Nggak cuma UGM. Nanti kalau
sudah selesai tugas di sini, sampean kuliah di Jogja, siapa tahu ketemu jodoh.
Hahahaha…”, canda Pak Amir.
“Pak
Amir bisa aja. Aamiin, Pak. Doakan nggih, Pak. Siapa tahu? Saya sebenarnya juga
kepengen kuliah di sini. Katanya kan ada PGSD ya, Pak. Nah, pengen banget saya
Pak masuk jurusan itu. Tapi katanya juga susah masuknya, saingannya banyak.
Hahaha!”
“Yakin
saja, Mas. Bapak doakan, kalau memang mau kuliah. Semoga dimudahkan sama Gusti
Allah”
“Aamiin,
jazakallahu khoiroo, Pak Amir. Oh iya, KKN-nya ini tinggal dimana? Biasanya
kalau KKN di daerah saya itu tinggal di rumah kepala dusun. Kok nggak tinggal
di rumah Bapak?”
“Woalah
Maas…sampean juga tahu to kalau rumah saya cuma segitu? Mahasiswa 12 orang itu
mau saya taruh mana? Hahaha. Nggak cukup, Mas. Mereka tinggal di rumah Pak
Andi, itu lho dekat Alfamart ujung jalan mau ke jalan propinsi. Ya sudah mas,
saya siang ini mau ke rumah mertua. Saya balik dulu. Assalamualaikum”,
“Wa’alaikumsalam”,
lagi-lagi Pak Amir adalah jamaah sholat terakhir yang meninggalkan masjid.
Kuiringi langkah beliau hingga tak tampak lagi.
Masih di atas karpet hijau shaf pertama, aku
membuka undangan itu perlahan. Aku cermati waktu dan tempatnya. Sebuah angan
melayang-layang. Aku teringat seseorang.
‘ayah kamu ingin kamu belajar di pondok kan, Hanif?’ Hanif diam.
‘kamu tetap mau kuliah? Pergilah ke pondok
dulu. Toh nanti masih bisa melanjutkan kuliah’ aku khawatir, kefahaman agamanya
belum mantap.
‘aku udah terlanjur mendaftar, mas. Udah
diterima dan udah bayar’ jawab Hanif seminggu kemudian.
‘jadi…kamu kuliah dimana? Jurusan apa?’ aku
khawatir, berjilbab pun rambutnya kemana-mana.
‘di UNY, mas’.
Sejak
itu Hanif pergi dan nomornya tidak bisa dihubungi. Aku juga pergi. Aku banyak berharap. Ada Hanif di sini. Ya
Allah, tiba-tiba aku rindu.
“Mas
Rosyiid, mahasiswa yang KKN di sini ada anak PGSD juga lho, sampean bisa
tanya-tanya. Saya pergi dulu, mas. Assalamualaikum” Pak Amir membuatku kaget.
Aku melambaikan tangan.
“Wa’alaikumsalam.
Hati-hati di jalan, Pak!”
***
Rumah
Pak Andi tak seperti biasanya yang sepi dengan pintu yang selalu tertutup
rapat. Malam ini keadaan itu berbalik. Kulihat beberapa tokoh masyarakat dusun
seperti ketua RW, ketua RT, ketua karang taruna, dan ketua komunitas-komunitas
lainnya telah hadir. Pintu rumah Pak Andi dibiarkan terbuka lebar. Tampak
beberapa mahasiswa beralmamater biru lalu lalang di dalam. Beberapa yang lain
menyambut kedatangan kami. Aku cemburu. Pada jas biru itu.
Ba’da
Isya, kami lengkap berkumpul di ruang tengah kediaman Pak Andi. Pandanganku
menyisiri satu persatu mahasiswa yang duduk rapi di hadapanku.
“Mahasiswa
UNY itu ribuan. Seangkatan ada berapa mas?” tanya seorang warga.
“Banyak.
Pak. Enam ribuan lebih” jawab seorang mahasiswa berambut keriting.
“Ini
cuma 12 orang. Lainnya KKN di mana?” tambah yang lain.
“Banyak
yang masih di lingkup DIY, beberapa ada yang di Magelang, Klaten, luar jawa,
bahkan luar negeri Pak” jawab mahasiswa berambut keriting lagi. Mereka lalu memperkenalkan diri satu-satu.
Tidak
ada Hanif.
“Mas
Rosyid, nanti sampean bawa motor saya, ya? Saya bareng Mbah Jamal mau ambil
cetakan batako di rumahnya Mas Rizal dulu, takut lupa lagi”, bisik Pak Amir.
Aku mengangguk.
“Mas
Rosyid!” seorang mahasiswa memanggilku saat aku hendak menstarter sepeda motor.
Dia yang berambut keriting, tersenyum ramah dan mendekatiku.
“Hampir
lupa Mas, saya. Begini, besok sore ada TPA kan, ya? Beberapa dari kami mau
gabung nih, sekalian bahas proker kami di TPA. Bisa, Mas?” lanjutnya.
“Siap
Mas!!” Mahasiswa berambut keriting yang kuketahui bernama Rifky itu tersenyum
semakin lebar.
“Terima
kasih banyak, Mas. Terima kasih. Hati-hati di jalan”, aku pun meninggalkannya. Berhenti di depan alfamart. Masuk, biar dapat
ucapan selamat malam. Aku
menuju meja kasir sambil membawa sebotol shampoo dan beberapa batang sabun di
tangan. Rupanya masih antri.
“Ini
kembaliannya, Mas. Terima Kasih…” ucap Mbak kasir ramah.
“Silakan
Mbak….” Sapa Mbak Kasir pada antrian di belakangku.
“MasyaAllah!!!”
aku terhenyak melihat siapa yang sedari tadi berdiri di belakangku. Dua
perempuan beralmamater biru. Tak tampak logo di sakunya karena tertutup jilbab
yang menjuntai panjang. Dia pun spontan menoleh ke arahku.
“MasyaAllah,
Mas Rosyid?” pekiknya.
“Hanif?”
“Yuk,
Hanif. Cepat, cepaaat…” temannya menarik lengan Hanif.
“Eh,
assalamualaikum, Mas Rosyid!”
Mereka
segera melaju kencang ke arah jalan propinsi. Sepertinya buru-buru. Kutatap dari jauh. Dia juga masih memandang ke
arahku. Jilbab ungu lebarnya menciptakan siluet, berkelebat tertiup angin.
“Wa’alaikumsalam,
Hanif”, Hanif
ada di sini. Dekat.
Tag :
Lomba Menulis Cerpen

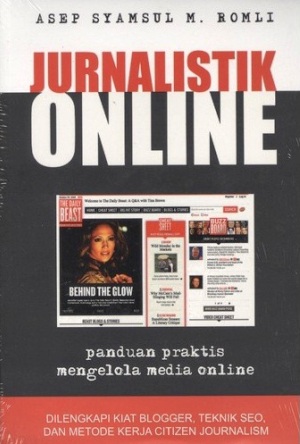

0 Comments for "Dekat Oleh - Heni Kusuma - Lomba Menulis Cerpen"